Aku ini binatang jalang dari kumpulannya yang terbuang
…..
Siapa yang tak kenal penggalan sajak diatas? Bahkan bocah-bocah berseragam putih merah akan dapat menyebutkan nama sang penyair dengan tepat. Begitu pula para ibu rumah tangga, sopir taksi, tukang kredit, juragan minyak tanah, pegawai rumah sakit, dukun jadi-jadian, penyewa topeng monyet, atau barangkali juga kuli dermaga yang pernah mengalami drop out saat kenaikan kelas dua di SLTP tiga puluh tahun lalu.
Jika dicari-cari sebabnya, pasti akan tersebut banyak jawaban; dari yang paling tepat, hingga yang sok dikait-kaitkan.Padahal saya yakin, pada jamannya, sebenarnya ada beberapa penyair yang tak kalah elok. Namun mengapa Chairil Anwar tampak yang sangat mencolok? Mengapa hanya puisi ‘jalang’ itu yang terdapat dalam buku-buku wajib diktat bahasa Indonesia? Apakah ini mengandung semacam siasat politik atau memang murni sebuah prestasi?
Puisi, meski telah eksis sejak jaman Mesopotamia, namun seringkali menjadi sajian eksklusif yang sebenarnya tak banyak dinikmati, melainkan hanya beberapa saja yang memang senang, cinta setengah mati, atau banyak paham tentang puisi. Mungkin dikarenakan puisi kerap menggunakan ungkapan-ungkapan bersayap, yang membuat orang-orang yang sudah banyak masalah dalam hidupnya jadi enggan untuk mencari-cari tahu makna tersirat atau keindahan dari puisi.
 Dari kubu yang lain, sebenarnya para penyuka puisi atau bahkan para penyair itu sendiri tak sedikit yang mencoba setia dengan seleranya. Entah karena mereka memang memutuskan untuk giat menyelami puisi dengan rasa cinta yang pekat, atau sekedar menikmati kata-kata indahnya yang berirama, yang kedengaran merdu di telinga, juga di hati. Selain itu, jangan pernah lupa bahwa puisi pun adalah bentuk tulisan yang lebih banyak melibatkan rasa, mengandung emosi. William Wordsworth sendiri mempunyai gagasan bahwa puisi adalah pernyataan perasaan yang imajinatif, yaitu perasaan yang direkakan atau diangankan. Barangkali itu sebab puisi memiliki peluang untuk lebih mudah disukai dan dicintai. Karena mereka sesungguhnya lebih dekat dengan perasaan, menerjemahkan kegelisahan jiwa melalui jalan keindahan.
Dari kubu yang lain, sebenarnya para penyuka puisi atau bahkan para penyair itu sendiri tak sedikit yang mencoba setia dengan seleranya. Entah karena mereka memang memutuskan untuk giat menyelami puisi dengan rasa cinta yang pekat, atau sekedar menikmati kata-kata indahnya yang berirama, yang kedengaran merdu di telinga, juga di hati. Selain itu, jangan pernah lupa bahwa puisi pun adalah bentuk tulisan yang lebih banyak melibatkan rasa, mengandung emosi. William Wordsworth sendiri mempunyai gagasan bahwa puisi adalah pernyataan perasaan yang imajinatif, yaitu perasaan yang direkakan atau diangankan. Barangkali itu sebab puisi memiliki peluang untuk lebih mudah disukai dan dicintai. Karena mereka sesungguhnya lebih dekat dengan perasaan, menerjemahkan kegelisahan jiwa melalui jalan keindahan.
Namun sejak jaman Homer hingga Pablo Neruda, jaman angkatan 45 hingga angkatan reformasi, toh perkembangan puisi hanya begitu-begitu saja. Puisi seringkali menjadi sajian eksklusif yang dimamah sebagian orang yang memang menyenanginya atau berniat sungguh-sungguh mencari-cari dan menyelaminya. Di samping itu, barangkali kita pun boleh menyalahkan media dan kesempatan yang kerap menganaktirikan puisi. Itu sebab para penulis fiksi memiliki lebih banyak peluang untuk lebih populer, pun terlihat bahwa massa mereka lebih besar dibanding massa para penyair. Orang awam akan dengan mudah menyebutkan sepuluh pengarang novel daripada sepuluh penyair. Bahkan sebagian antusias memperbincangkan isi cerita novel-novel populer bak menggosipkan artis panas. Namun ketika membicarakan puisi, mereka akan menjawab, “puisi yang mana? siapa yang mengarang? manusia juga – kah?” Di antara seratus buku yang terpajang rapi di deretan rak toko buku besar, hanya terdapat satu atau dua buku puisi yang terselip diantaranya.
Pertanyaannya, sejak kapan masa itu berakhir? Jangan-jangan, generasi (ter)kini bahkan telah lupa bahwa puisi pernah menjadi sebuah seni yang cukup eksklusif. Pasalnya, puisi kini telah menjadi semacam gaya hidup yang mulai banyak disukai siapa saja, sudah merambah ranah konsumsi awam — meski masih dalam bentuk yang terbatas. Kita patut berterima kasih pada kecanggihan teknologi IT. Di era yang semakin transparan ini, kata-kata yang terbungkus dalam bait-bait sajak bukan lagi milik para penyair-penyair yang telah di’baiat’ menjadi seniman secara resmi – melainkan milik siapa saja. Puisi dapat ditemukan dengan mudah dimana saja, dan siapapun juga dapat dengan mudah belajar darinya. Ibarat roti, kini tak lagi dikonsumsi oleh para orang kaya seperti pada jaman penjajahan dulu, melainkan sudah dinikmati oleh kalangan manapun.
Sebut saja twitter, salah satunya yang menggiatkan gerakan sajak menyajak. Media jejaring sosial yang telah menghubungkan sekian juta penggunanya dengan memperpendek jarak hubungan ini berjasa amat besar dalam mensosialisasikan puisi — meski dalam keterbatasan 140 karakter. Saat ini, begitu mudah kita temukan kata-kata indah yang memantul-mantul di linimasa. Sajak dalam 140 karakter itu seolah merupakan sebuah aliran arus tersendiri, yang mengungkapkan luapan perasaan dengan cara yang lebih elegan, lebih anggun, lebih memikat. Tak heran jika para pemilik akun yang kerap menggulirkan sajak-sajak singkat itu lekas menjadi primadona di dunia twitter. Mereka mudah menggapai massa, meraup banyak pengikut melalui kepiawaiannya menyentil emosi dengan kata-kata indah. Untuk saat ini, tanpa twitter, sajak-sajak indah itu takkan lekas sampai ke hati sekian puluh ribu pengguna twitter yang beragam latar belakang.
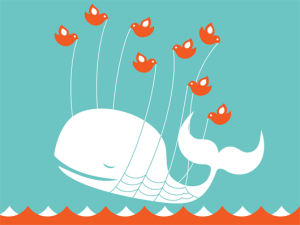 Kendati demikian, twitter sebagai media memang hanyalah sebuah alat yang notabene benda mati. Bagaimanapun, fenomena gerakan sajak yang sepertinya mulai meng’tsunami’ ini pun tak lepas dari andil para pemilik akun yang konsisten menelorkan sajak-sajak. Tanpa usaha yang telaten, gerakan sajak takkan sebesar ini. Tanpa Hasan Aspahani, Aan Mansyur, Joko Pinurbo, maupun para penggiat puit-tweet lainnya, masyarakat awam yang kini mulai gemar bersosialisasi melalui twitter takkan mengenal dan memamah sajak dengan sedemikian rakus. Harap dimaklumi jika tren puit-twit berbiak dan bertumbuh kembang dengan pesat. Andil terbesar, salah satunya berkat jasa para penggiat yang gigih. Puisi tak lagi milik segelintir orang, melainkan milik siapa saja yang (sudi) meminatinya. Bukan lagi makanan yang sukar dikunyah, melainkan jenis snack yang ramah sekaligus renyah.
Kendati demikian, twitter sebagai media memang hanyalah sebuah alat yang notabene benda mati. Bagaimanapun, fenomena gerakan sajak yang sepertinya mulai meng’tsunami’ ini pun tak lepas dari andil para pemilik akun yang konsisten menelorkan sajak-sajak. Tanpa usaha yang telaten, gerakan sajak takkan sebesar ini. Tanpa Hasan Aspahani, Aan Mansyur, Joko Pinurbo, maupun para penggiat puit-tweet lainnya, masyarakat awam yang kini mulai gemar bersosialisasi melalui twitter takkan mengenal dan memamah sajak dengan sedemikian rakus. Harap dimaklumi jika tren puit-twit berbiak dan bertumbuh kembang dengan pesat. Andil terbesar, salah satunya berkat jasa para penggiat yang gigih. Puisi tak lagi milik segelintir orang, melainkan milik siapa saja yang (sudi) meminatinya. Bukan lagi makanan yang sukar dikunyah, melainkan jenis snack yang ramah sekaligus renyah.
Kendati demikian, setiap kejadian selalu memiliki efek positif maupun negatif. Tak terkecuali dengan munculnya persepsi yang baik atau mungkin tidak baik. Namun jika saya boleh memilih, maka saya akan lebih senang menghidupkan pikiran positif atas gerakan pui-twit yang sedang gencar. Puisi adalah budaya yang baik, dan mem-puisikan masyarakat pun bukan perbuatan tercela. Hati memerlukan selingan, rasa butuh keindahan. Jika masing-masing dari kita senantiasa mendukung untuk saling mengajarkan, saling menguatkan, dan saling menghibur, alangkah indah dan damainya dunia ini.
Satu ungkapan terakhir yang saya kutip dari @hurufkecil — demi menyambut era puittwit-puittwit yang bertebaran,
“Mari merayakan kata-kata!” 😀

